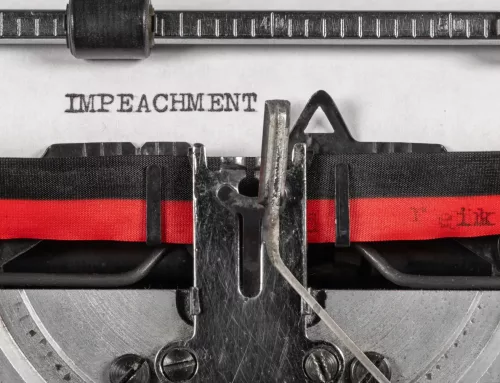Ilustrasi. [Source: Canva]
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman resesi yang mengintai, pemerintah Indonesia justru bersiap menerapkan kebijakan yang kontroversial: menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per Januari 2025. Kebijakan yang mengacu pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7/2021 ini menyiratkan sebuah paradoks fundamental dalam pendekatan fiskal pemerintah.
Kenaikan bertahap dari 10% menjadi 11%, dan kini menuju 12%, pada dasarnya mencerminkan kegagalan sistemik dalam reformasi perpajakan Indonesia. Alih-alih melakukan reformasi struktural untuk memperluas basis pajak penghasilan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memilih jalan pintas dengan membebankan konsumen melalui pajak konsumsi yang bersifat regresif.
Argumentasi pemerintah bahwa kenaikan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat perlu dikritisi secara mendalam. Klaim bahwa kenaikan hanya akan berdampak 0,9% pada harga barang dan jasa mengabaikan efek berantai dalam struktur ekonomi. Ketika biaya produksi naik akibat PPN yang lebih tinggi, produsen cenderung mengompensasi kenaikan tersebut dengan menaikkan harga lebih dari sekadar dampak langsung PPN. Fenomena ini dikenal dalam teori ekonomi sebagai efek multiplier yang dapat menciptakan spiral inflasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, timing implementasi kebijakan ini patut dipertanyakan. Indonesia masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi, sementara ancaman resesi global masih membayangi. Bank Dunia dan IMF telah memperingatkan potensi perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak signifikan pada negara berkembang. Dalam konteks ini, menaikkan PPN justru dapat menjadi katalis yang memperparah situasi ekonomi.
Dari perspektif keadilan sosial, kenaikan PPN memberikan pukulan telak bagi kelompok menengah ke bawah. PPN merupakan pajak regresif dimana semua konsumen membayar tarif yang sama terlepas dari kemampuan ekonomi mereka. Akibatnya, proporsi beban pajak terhadap pendapatan justru lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan pajak yang diamanatkan konstitusi.
Pembebasan PPN untuk beberapa komoditas pokok dan penerapan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk beberapa produk strategis sebenarnya merupakan pengakuan implisit bahwa kebijakan ini bermasalah. Jika pemerintah yakin kebijakan ini tepat, mengapa perlu memberikan berbagai pengecualian? Kompleksitas administrasi yang ditimbulkan dari pengecualian ini juga berpotensi menciptakan celah untuk penghindaran pajak dan korupsi.
Sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, akan menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, mereka harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat PPN yang lebih tinggi untuk bahan baku dan operasional. Di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat akan mengakibatkan penurunan permintaan. Kondisi ini dapat memicu gelombang penutupan usaha dan PHK yang akan memperparah masalah pengangguran.
Dari perspektif hukum, kebijakan ini berpotensi mendapat tantangan konstitusional. Pasal 23A UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak, namun dengan syarat untuk kemakmuran rakyat. Ketika sebuah kebijakan pajak justru berpotensi menurunkan kesejahteraan mayoritas penduduk, legitimasinya dapat dipertanyakan. Hal ini membuka peluang untuk gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Alih-alih menaikkan PPN, pemerintah seharusnya fokus pada reformasi perpajakan yang lebih fundamental. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak penghasilan melalui perbaikan sistem administrasi dan database perpajakan. Kedua, perluasan basis pajak dengan memanfaatkan digitalisasi dan big data untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Ketiga, pengetatan belanja negara yang tidak produktif untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih luas.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dari sektor-sektor yang selama ini belum optimal. Sektor digital economy, misalnya, masih menyimpan potensi pajak yang signifikan. Begitu juga dengan sektor properti mewah dan barang-barang luxury yang selama ini belum terjangkau sistem perpajakan secara efektif. Fokus pada sektor-sektor ini akan memberikan dampak yang lebih adil dibandingkan menaikkan PPN yang membebani semua lapisan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak juga menjadi isu krusial yang sering terabaikan. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan sulit meningkat jika tidak ada jaminan bahwa uang pajak digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Audit dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana pajak seharusnya menjadi prioritas sebelum memutuskan menaikkan tarif pajak apapun.
Pertimbangan timing implementasi kebijakan ini juga perlu dikaji ulang. Jika memang kenaikan PPN tidak dapat dihindari, setidaknya implementasinya perlu menunggu kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, dan daya beli masyarakat harus menunjukkan tren positif yang stabil sebelum kebijakan ini diterapkan.
Kesimpulannya, kenaikan PPN menjadi 12% mencerminkan pendekatan yang terlalu simplistic terhadap masalah kompleks perpajakan Indonesia. Kebijakan ini lebih mencerminkan kebutuhan jangka pendek penerimaan negara dibanding reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan alternatif yang lebih progresif dan berkeadilan. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, kenaikan PPN hanya akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat tanpa memberikan solusi struktural bagi sistem perpajakan Indonesia.