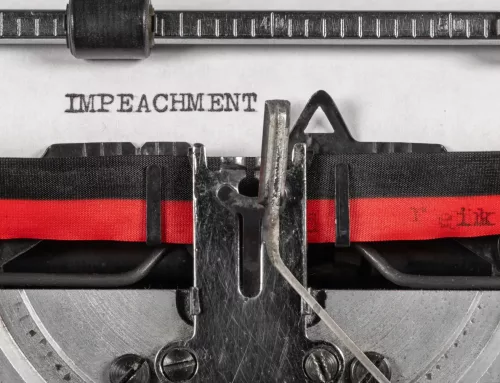Ilustrasi. [Source: Canva]
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jumat (04/01/2024), telah membuka babak baru dalam dinamika profesi advokat di Indonesia. Putusan yang mengizinkan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi advokat prodeo/pro bono ini menimbulkan berbagai pertanyaan fundamental tentang independensi profesi advokat dan integritas sistem hukum Indonesia.
Ketika membaca putusan tersebut, kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang diciptakan Mahkamah Konstitusi: bagaimana mungkin seorang PNS yang terikat loyalitas pada pemerintah dapat sekaligus menjalankan profesi yang mensyaratkan independensi penuh? Inilah dilema konstitusional yang tampaknya luput dari pertimbangan mayoritas hakim konstitusi.
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu landasan argumentasi dalam putusan tersebut telah ditafsirkan secara keliru. Pengabdian kepada masyarakat dalam konteks Tri Dharma seharusnya tidak dimaknai sebagai justifikasi untuk menjalankan praktik profesi advokat, bahkan dalam konteks prodeo/pro bono sekalipun. Pengabdian masyarakat dalam dunia akademik memiliki spektrum yang jauh lebih luas dan tidak harus bersinggungan dengan praktik advokasi langsung di pengadilan.
Harusnya Hakim Mahkamah Konstitusi ingat bahwa konflik kepentingan terjadi ketika seseorang memiliki multiple loyalties. Dalam konteks dosen PNS yang menjadi advokat, principal-agent problem menjadi tidak terhindarkan – bagaimana mungkin seorang agen dapat melayani dua principal (negara dan klien) dengan kepentingan yang berpotensi bertentangan secara efektif?
Lebih jauh lagi, putusan ini mengabaikan aspek fundamental dari profesi advokat sebagai profesi bebas dan mandiri. Undang-Undang Advokat tidak tanpa alasan melarang pegawai negeri menjadi advokat. Larangan ini merupakan manifestasi dari prinsip independensi yang menjadi roh dari profesi advokat. Seorang advokat harus bebas dari intervensi dan kepentingan apapun, termasuk kepentingan negara, dalam membela kliennya.
Permasalahan akan menjadi semakin kompleks ketika kita berbicara tentang mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik. Bagaimana mungkin seseorang bisa tunduk pada dua rezim pengawasan yang berbeda – kode etik PNS dan kode etik advokat – yang masing-masing memiliki landasan filosofis dan orientasi yang berbeda? Ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan menyangkut integritas sistem hukum secara keseluruhan.
Seorang filsuf hukum Amerika, Lon L. Fuller, menekankan bahwa profesi hukum memiliki moralitas internal yang harus dijaga. Hal yang sama juga dipertegas oleh filsuf berkebangsaan Inggris, Bernard Williams, mengatakan bahwa integritas profesional membutuhkan konsistensi peran. Ketika seorang PNS harus menjalankan dua sistem nilai dan kode etik yang berbeda secara simultan, integritas profesional ini menjadi sulit dipertahankan.
Praktek di berbagai negara seperti yang diterangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Daniel Yusmic P. Foekh dalam dissenting opinion pada putusan tersebut bisa menjadi cermin bagi kita. Vietnam, Cina, dan India dengan tegas melarang pegawai negeri untuk menjadi advokat. Bahkan di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih mapan, pemisahan antara fungsi publik dan profesi advokat tetap dijaga dengan ketat. Ini bukan tanpa alasan – pengalaman mereka menunjukkan bahwa pemisahan ini penting untuk menjaga integritas kedua institusi.
Putusan MK ini juga berpotensi menciptakan preseden yang problematik. Jika dosen PNS diizinkan menjadi advokat, meskipun terbatas pada kasus prodeo/pro bono, apa yang mencegah profesi PNS lainnya untuk menuntut hal yang sama? Bagaimana dengan peneliti hukum di lembaga pemerintah? Pemberian pengecualian semacam ini bisa membuka kotak pandora yang sulit ditutup kembali.
Aspek pengawasan juga menjadi masalah serius. Pembatasan “hanya untuk prodeo/pro bono” dalam praktiknya akan sangat sulit diawasi. Siapa yang akan memastikan bahwa seorang dosen PNS yang berpraktik sebagai advokat benar-benar tidak menerima honorarium? Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya? Putusan MK tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan krusial ini.
Yang lebih mengkhawatirkan, putusan ini berpotensi melemahkan independensi profesi advokat secara keseluruhan. Ketika kita membuka celah bagi aparatur negara untuk masuk ke dalam profesi ini, kita membuka pintu bagi potensi intervensi negara – baik langsung maupun tidak langsung – terhadap profesi yang seharusnya bebas dan mandiri.
Dissenting opinion dari dua hakim konstitusi dalam putusan ini justru menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat profesi advokat dan implikasi sistemik dari pengecualian yang diberikan. Mereka dengan tepat mengingatkan bahwa terdapat alternatif lain bagi dosen PNS untuk berkontribusi dalam praktik hukum tanpa harus menjadi advokat, misalnya melalui klinik hukum universitas atau sebagai ahli di pengadilan.
Solusi yang lebih tepat sebenarnya adalah dengan memperkuat peran lembaga bantuan hukum universitas dan klinik hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ini bisa menjadi wadah bagi dosen untuk mentransfer pengetahuan teoritisnya ke dalam praktik, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tanpa harus mengorbankan prinsip independensi profesi advokat.
Ke depan, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi praktis dosen hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum kita. Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan model alternatif seperti sabbatical leave khusus bagi dosen hukum untuk praktik di firma hukum atau lembaga bantuan hukum, dengan status non-PNS sementara.
Pada akhirnya, putusan MK ini mengingatkan kita bahwa solusi pragmatis jangka pendek tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental. Independensi profesi advokat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.